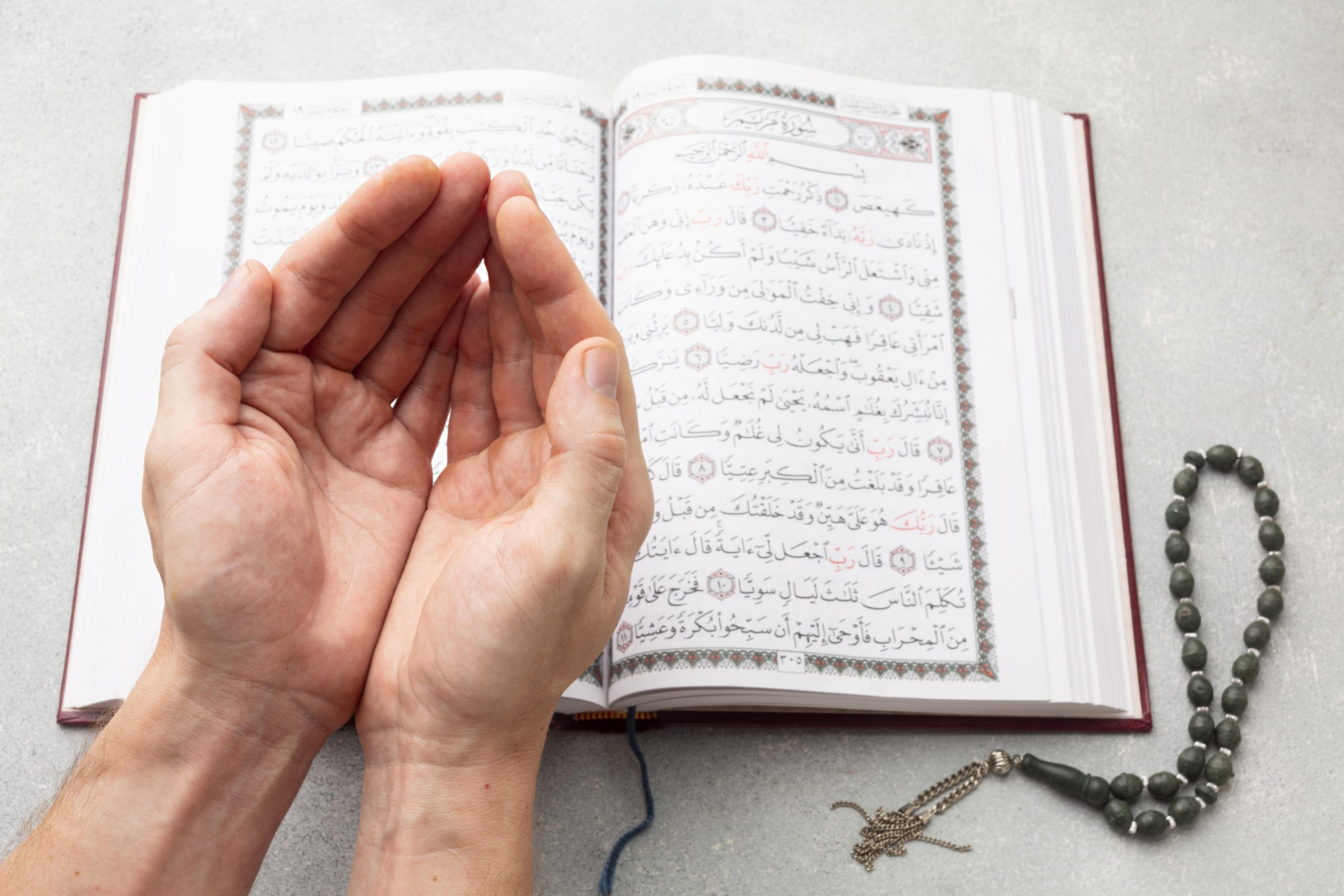
Al-Qur’an, sebagai kitab suci, menyimpan dua kategori ayat yang menjadi inti dari kajian Ulumul Qur’an: ayat-ayat Muhkamat dan Mutasyabihat. Keberadaan keduanya merupakan sebuah anugerah sekaligus tantangan bagi keimanan. Sebagaimana Allah tegaskan:
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ
“Dialah yang menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur’an); di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab, dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat.” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 7)
Kemampuan membedakan dan menyikapi kedua jenis ayat ini menjadi krusial. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian akidah agar tidak tergelincir pada tasybīh (menyerupakan Allah dengan makhluk) ataupun ta‘ṭīl (menafikan sifat-sifat-Nya). Ini adalah proses mendialogkan nalar (aql) dengan kepatuhan pada wahyu (naql).
- Hakikat Muhkamat dan Mutasyabihat dalam Kalam Ulama
Para ulama klasik telah merumuskan definisi (ibaroh) untuk memahami esensi dari kedua jenis ayat ini.
- Ayat Muhkamat: Fondasi yang Kokoh
Kata Muhkam (المُحْكَم) secara bahasa berarti sesuatu yang dikokohkan atau dicegah dari keraguan. Inilah fondasi Al-Qur’an yang disebut sebagai Ummul Kitab (Induk Kitab).
- Menurut ulama salaf seperti Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat Muhkamat adalah ayat yang maknanya lugas, gamblang, dan tidak mengandung keraguan interpretasi.
- Ulama lain, seperti Ali bin Abi Thalhah, merincinya sebagai ayat-ayat yang secara eksplisit mengatur hukum (halal-haram), kewajiban (fara’id), dan batasan (hudud). Intinya, Muhkamat adalah ayat yang maknanya dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan rujukan lain.
- Ayat Mutasyabihat: Samudera Makna yang Dalam
Kata Mutasyabih (المُتَشَابِه) berarti adanya keserupaan atau kesamaran. Ayat-ayat ini sengaja diturunkan dengan makna yang tidak langsung.
- Ibnu Abbas dalam riwayat lain menyebutnya sebagai ayat yang memiliki banyak wajah penafsiran (wujuh) atau maknanya tersembunyi.
- Contoh paling umum yang disepakati ulama klasik adalah huruf-huruf Muqaththa’ah (potongan huruf di awal surah), hakikat Hari Kiamat, dan ayat-ayat yang menyangkut sifat Allah (sifāt khabariyyah) seperti Istiwa’ (Bersemayam) atau Yadullah (Tangan Allah).
- Dua Pendekatan Utama dalam Menyikapi Mutasyabihat
Perbedaan pandangan mengenai siapa yang dapat mengetahui takwil ayat Mutasyabihat melahirkan dua metodologi besar di kalangan ulama:
- Pendekatan Tafwidh (Mazhab Salaf)
Metode ini, yang dipegang oleh mayoritas ulama salaf (terdahulu) seperti Imam Malik bin Anas, memilih jalan aman dengan:
- Mengimani lafazhnya sebagaimana datangnya.
- Menyerahkan (tafwidh) hakikat maknanya kepada Allah semata.
- Mereka meyakini makna lahiriahnya, namun menolak membayangkan “bagaimana”-nya (kaifiyyah) dan menolak menyerupakannya dengan makhluk.
- Kalam (ungkapan) Imam Malik sangat masyhur: “Al-Istiwa’ ma’lum (Bersemayam itu diketahui maknanya), wal kaifu majhul (dan bagaimana hakikatnya tidak diketahui), wal imanu bihi wajib (dan mengimaninya wajib), was su’alu ‘anhu bid’ah (dan bertanya tentangnya adalah bid’ah).”
- Pendekatan Ta’wil (Mazhab Khalaf)
Metode ini dianut oleh banyak ulama khalaf (terkemudian) dan sebagian ulama salaf. Mereka berpandangan bahwa ar-rasikhun fil ‘ilmi (orang yang ilmunya mendalam) memiliki kapasitas untuk:
- Melakukan Ta’wil, yaitu mengalihkan makna lahiriah (yang berpotensi tasybīh) kepada makna metaforis (majazi) yang paling sesuai dengan keagungan Allah.
- Tujuannya adalah untuk menyucikan Allah (tanzih) dari sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya.
- Sebagai contoh, Yadullah (Tangan Allah) ditakwilkan sebagai kekuatan atau nikmat Allah, agar sesuai dengan ayat Muhkamat “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya” (QS. Asy-Syura: 11).
- Dua Arsitek Akidah Ahlus Sunnah
Formulasi akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam menyeimbangkan dua pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh dua imam besar:
- Imam Abū al-Ḥasan al-Asy‘arī (260–324 H)
Beliau adalah tokoh dari Basrah yang merumuskan jalan tengah setelah meninggalkan paham Mu’tazilah. Melalui karya seperti al-Ibānah dan al-Luma‘, Imam Al-Asy’ari menjembatani dalil wahyu (naql) dengan logika (aql). Beliau pada dasarnya mengafirmasi metode tafwidh ala salaf, namun membuka ruang bagi ta’wil yang shahih sebagai perangkat untuk membantah paham yang menyimpang dan menjaga akidah umat.
- Imam Abū Manṣūr al-Māturīdī (w. 333 H)
Ulama besar dari Samarkand ini, melalui Kitāb at-Tawḥīd dan Ta’wīlāt al-Qur’ān, dikenal mengedepankan nalar (aql) dalam bingkai wahyu (nash). Imam Al-Maturidi lebih cenderung menggunakan ta’wil secara sistematis untuk menjelaskan ayat-ayat Mutasyabihat, demi mencapai tanzih dan membuktikan keesaan Allah secara rasional.
Dengan berkaca pada kedua imam ini, kita belajar bahwa beriman membutuhkan ilmu, dan berilmu harus dilandasi iman. Ayat Muhkamat adalah pemandu yang kokoh, sementara ayat Mutasyabihat adalah lautan hikmah yang menuntut kita untuk berlayar dengan kompas akidah yang benar.



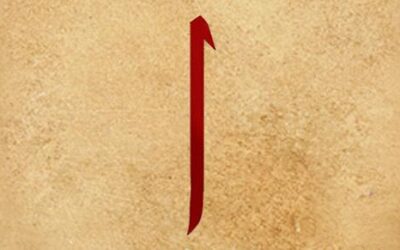
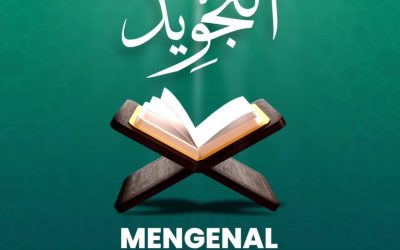



0 Komentar